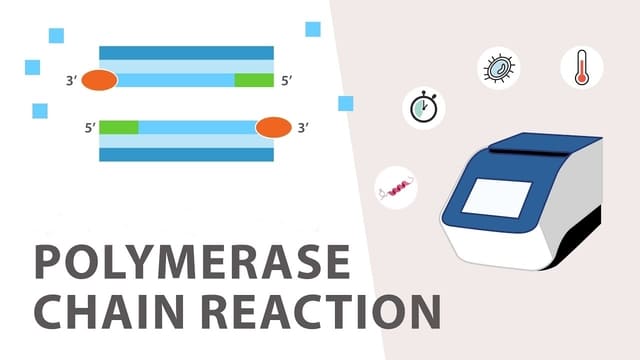Dimana ada manusia disitu ada bahasa. Pun juga sebaliknya. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Manusia bisa berkembang karena bahasa, keduanya bisa menyatu dalam segala aktivitas kehidupan. Terdapat pepatah melayu yang sangat populer, “Bahasa Menunjukkan Bangsa ” tampaknya sangat relevan untuk memahami bahasa dan hakikatnya secara utuh.
Tafsir ini menjadi benar berdasarkan teori hubungan antara pikiran, budaya, dan bahasa. Setiap bahasa merepresentasikan pengalaman dan pikiran seseorang. Orang yang sedang kacau pikirannya, hampir bisa dipastikan bahasanya juga kacau. Atau sebaliknya, orang yang bahasanya kacau, biasanya pikirannya juga sedang kacau. Dengan demikian betapa pentingnya bahasa bagi kehidupan manusia.
Berbahasa, dalam arti berkomunikasi, dimulai dengan membuat enkode semantik dan enkode gramatikal di dalam otak pembicara, dilanjutkan dengan membuat enkode fonologi. Dari serangkaian proses enkode tersebut, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan dekode fonologi, dekode gramatikal, dan dekode semantik pada pihak pendengar yang terjadi di dalam otaknya. Dengan kata lain, berbahasa adalah penyampaian pikiran atau perasaan dari orang yang berbicara mengenai masalah yang dihadapi dalam kehidupan budayanya (Abdul Chaer, 2002)
Terkait dengan ini, Confusius pernah mengingatkan kepada kita akan pentingnya bahasa yang benar dan jelas agar tidak menimbulkan kekacauan. Saking pentingnya bahasa di mata Confusius, maka ketika ia ditanya apa yang mesti pertama dilakukannya seandainya berkesempatan memimpin negara adalah “membangun bahasa masyarakat”. Menurutnya, kekacauan hampir sebagian besar berawal dan berakhir pula dengan bahasa.
Bahasa dan praktik kebahasaan banyak terkait dengan faktor sosial, psikologis, filosofis, kultur, dan bahkan biologis.
Budaya suatu bangsa terungkap jelas melalui praktik kebahasaannya. Pemilihan kata, gaya bahasa, intonasi, nada, bahkan gestur ketika berbahasa menyiratkan makna yang berbeda-beda. Kendati manusia bebas berbahasa, dalam kenyataannya toh dia terikat dengan siapa, di mana, kapan, dan dengan target apa. Tema yang sama akan disampaikan dengan cara yang berbeda kepada orang yang berbeda. Kesopanan dan kesantunan seseorang lantas sering kali diukur dengan bagaimana dia berbahasa.
Minat orang terhadap bahasa bisa dilacak sejak zaman Yunani Kuno, abad kelima sebelum Masehi, ketika filsuf menyadari akan banyaknya fungsi bahasa. Para filsuf Yunani memandang bahasa sebagai alat untuk mencari dan mengungkapkan kebenaran, untuk mengekspresikan hal-hal yang bersifat artistik, dan untuk persuasi. Orang-orang Yunani Kuno mempunyai bakat ingin tahu tentang hal yang oleh orang lain dianggap lazim dan semestinya. Barangkali karena lazimnya itu, kita jarang memperhatikan bahasa secara utuh dan menganggapnya sebagai hal yang remeh.
Mayarakat Yunani Kuno sangat berani dan gigih membuat spekulasi mengenai asal mula, struktur, sejarah, dan peran bahasa. Sikap mental ini mencapai puncaknya ketika orang Athena yang hidup pada abad ke-5 memandang bahasa sebagai instrumen utama untuk mencapai tujuan tertentu, yang konkret dan praktis. Karenanya, bahasa dianggap sebagai senjata ampuh dalam percaturan politik.
Menurut Derrida, seorang tokoh post modernisme, bahasa bukan sekadar urut-urutan kata yang diatur secara gramatikal oleh tata bahasa dan dipilih secara bebas oleh penuturnya. Bahasa adalah manifestasi totalitas pikiran manusia yang terkait dengan kondisi, setting, maksud yang hendak disampaikan, serta target yang akan diraih. Ide ini terus berkembang tergantung pada siapa yang mengucapkannya. Makna kata lantas tidak hanya dibawa oleh kata itu sendiri, tetapi oleh siapa, di mana, kepada siapa dan kapan kata itu diucapkan.
Tampaknya fungsi bahasa yang demikian tersebut masih berlaku saat ini, ketika para elit politik menggunakan bahasa sebagai senjata perjuangan politiknya. Siapa yang piawai bermain ‘retorika’, maka dia memiliki kans besar untuk menang dalam percaturan politik. Karena bahasa pada hakekatnya adalah sistem reproduksi ideasional, maka setiap kata mengandung makna.
Terkait dengan peran bahasa, jauh-jauh hari Habermas telah mengingatkan bahwa proses-proses sosial politik tidak sekedar beranyamkan praksis kerja, tetapi komunikasi, yakni bahasa. Oleh karena itu, pagelaran kekuasaanpun tidak terbatas pada pengendalian sarana teknis reproduksi material, tetapi tak kalah pentingnya adalah upaya-upaya manipulasi terhadap sistem-sistem simbol dan reproduksi ideasional (Raharjo, 2002)
Perkembangan peran dan fungsi bahasa tersebut terus melebar menyusul kelahiran post-modernisme dan post strukturalisme dalam filsafat modern.
Dimana bahasa dan praktik berbahasa tidak dapat lagi dimengerti dalam perspektif konvensional, yakni sekedar sebagai alat komunikasi. Namun semakin disadari bahwa bahasa hadir sebagai representasi dari ruang pagelaran kekuasaan. Bahasa lantas disimak pula sebagai ruang berlangsungnya penggelaran berbagai kepentingan, kekuasaan, dan kekuatan.
Sebagai realitas simbolik, bahasa tampaknya tidak bisa dipisahkan dari dunia batin pemakainya dan kondisi sosial politik masyarakat penuturnya. Situasi sosial yang kondusif akan melahirkan simbol-simbol yang mantap dan stabil dalam kosakatanya. Sebaliknya, situasi yang tengah bergejolak dan tidak menentu seperti yang terjadi di tanah air belakangan ini, turut tercermin dalam ungkapan-ungkapan bahasa yang membingungkan, sarkastik, dan ambigu. Wajarkah ungkapan-ungkapan sarkastik seperti: cebonger, kampreter, kadrun, presiden pembohong,menteri dongo, drakula politik, garong APBN, dan masih seabrek lagi yang lainnya tersebut? Apalagi naskah drama sarkastik tersebut dimainkan dan dipertontonkah dalam ruang publik oleh seorang publik figur?
Ah entahlah, kunikmati saja secangkir kopi ini. Silahkan dilanjutkan dialektikanya.
Salam Santuy.